Yang aku tahu, kematian itu adalah usainya suatu perkara, tapi setelah itu perkara lainnya telah siap pula menunggu untuk dihadapi. Artinya, antara perkara yang satu dengan perkara lainnya merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan. Bagaimana pun manusia berusaha memutuskan rantai-rantai siklus itu tetapi siklus itu tidak akan pernah terputus. Akhir-akhir ini, sepertinya, banyak manusia yang berusaha mengingkari kodratnya, dan mereka merasa telah berhasil memutuskan siklus kehidupan yang diciptakan tuhan. Dan ketika aku katakan pada mereka bahwa mereka telah keliru, mereka malah marah dan aku diasingkan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka memperlakukanku seperti itu. Hal itulah yang selama ini menjadi polemik yang bergejolak dalam jiwaku.
Kingdon181 Cyber Area
Minggu, 03 Juni 2012
Maaf… Mak…!?
Cerpen DM. Thanthar
Nafas reformasi pun belum
mampu mengatasi kebobrokan negeri ini. Keangkuhan tembok-tembok sosial yang
memisahkan si kaya dengan si miskin makin mencakar langit. Akibatnya,
orang-orang makin mudahnya menjual moral mereka hanya untuk mencari kekayaan,
menumpuk-numpuk harta benda untuk suatu saat di pamerkan pada tamu-tamu yang
berkunjung ke rumahnya, walaupun tetangganya akan mati kelaparan.
Semakin hari, semakin banyak
makhluk yang disebut manusia itu terjerumus manjadi kaum pemuja harta, pemuja
dunia, dan menjadi budak dari apa yang mereka ciptakan sendiri. Mereka seakan
lupa akan kodratnya, lupa darimana mereka berasal dan kemana mereka akan
kembali setelah masa hidupnya yang singkat berakhir. Agaknya, bagi mereka,
setelah mati habislah perkara.
Aku tidak sepaham dengan
mereka. Bagiku, persoalan hidup tidaklah semudah itu. Lingkaran hidup makhluk
memang sederhana. Lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan
kemudian mati. Kira-kira seperti itulah lingkaran kehidupan yang utuh. Kalaupun
lingkaran kehidupan itu tidak utuh, maka tetap kematian yang menjadi muaranya.
Yang aku tahu, kematian itu adalah usainya suatu perkara, tapi setelah itu perkara lainnya telah siap pula menunggu untuk dihadapi. Artinya, antara perkara yang satu dengan perkara lainnya merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan. Bagaimana pun manusia berusaha memutuskan rantai-rantai siklus itu tetapi siklus itu tidak akan pernah terputus. Akhir-akhir ini, sepertinya, banyak manusia yang berusaha mengingkari kodratnya, dan mereka merasa telah berhasil memutuskan siklus kehidupan yang diciptakan tuhan. Dan ketika aku katakan pada mereka bahwa mereka telah keliru, mereka malah marah dan aku diasingkan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka memperlakukanku seperti itu. Hal itulah yang selama ini menjadi polemik yang bergejolak dalam jiwaku.
“Sampai kapan kau akan
bertahan dengan sikap dan pendirian seperti itu. Janganlah sok suci, sok alim,
karena dengan sikap yang seperti itu berarti kau merintis jalan menuju
keterasingan.” Suatu ketika seorang sahabatku yang bernama Dani pernah berkata
begitu padaku.
“Ku akui, prinsip hidup yang
kau pertahankan itu sangat bagus, sangat mulia. Tapi kau juga harus menyadari
bahwa sekarang zaman sudah berubah, masa telah berganti. Jadi kalau kau tidak
mencari tuah kepada yang menang dan meniru kepada yang sudah maka tidak akan
ada perubahan dalam hidupmu.” Sambungnya.
Aku hanya diam, tapi
memandangnya dengan tajam. Dia menghisap rokok, dan kemudian menghempaskan asapnya.
“Man, jangan terlalu banyak
pertimbangan. Hidup ini hanya sekali setelah itu mati. Apa kau memang tidak
ingin melakukan perubahan dalam hidupmu? Ingat Man, orang tuamu dan adik-adikmu
di kampung sangat menumpukan harapan mereka padamu. Bagaimana mungkin kau bisa
membantu biaya sekolah adik-adikmu, sedangkan untuk biaya hidupmu sendiri saja
masih pas-pasan.” Dani berhenti sejenak dan aku masih saja diam.
“Aku tahu, aku bisa menebak isi
fikiranmu, kau ingin mengatakan bahwa kau sudah merasa bahagia dengan hidup
seperti ini. Tapi aku juga tahu, bahwa sebenarnya kau pun sangat ingin memiliki
pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak. Aku hanya mau katakan, paling tidak
sebagai pertimbangan bagimu, bahwa jika kau tetap bersikeras hati mencari kerja
hanya dengan mengandalkan keahlianmu dan ijazahmu saja maka kau akan tetap
tertinggal. Bukankah kau sudah berkali-kali membuktikannya sendiri.” Ucapan Dani mulai mempengaruhiku, tapi aku
tetap diam.
“Jujur saja, dari dulu aku salut padamu. Kau rela
hidup pas-pasan demi mempertahankan sesuatu yang kau sebut dengan prinsip
hidup. Kau rela miskin harta demi kekayaan dan kemuliaan jiwa. Tapi cobalah kau
renungkan lagi, apakah kekayaan dan kemuliaan jiwamu itu bisa membantu dan
memberi kebahagiaan bagi keluargamu?”
Aku masih saja diam, namun
memori usang mulai membentang di mataku.
***
Wajah ayah dan emak terbayang
jelas di pelupuk mataku. Ayah yang telah semakin tua masih tetap gigih berusaha
untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dulu, masih ada tanah yang bisa
digarap ayah untuk sekedar kebutuhan sehari-hari, tapi kini tanah itu sudah
tidak ada lagi, dijualnya demi keinginannya untuk bisa menyekolahkan anaknya
sampai sarjana. Akibatnya, sekarang ayah harus menjadi buruh tani. Sehari-hari
ia bekerja di sawah dan ladang orang lain dengan upah yang sangat jauh di bawah
standar UMR. Untung saja emak bisa memahami kondisi itu dan tidak pernah
mengeluh dengan keadaan yang dihadapinya. Hanya saja di matanya nan bening
terpancar harapan yang sangat besar kepadaku.
“Man, kau harus belajar dengan
rajin. Tidak usah berfikir yang macam-macam, soal biaya untuk sekolahmu biar
ayah dan emak yang memikirkannya. Mak tidak ingin nanti kau dan adik-adikmu
hidup seperti ini juga. Kalian tidak boleh bodoh, kalian harus pintar, kalian
harus jadi orang.” Demikian nasihat emak saat aku masih sekolah dulu. Dan aku
hanya diam.
“Kalau kau sudah berhasil
nanti, maka kau tentu akan bisa pula membentu biaya sekolah adik-adikmu.”
“Iya Mak.” Jawabku singkat,
ketika itu.
***
“Hei, Man...!! Kok malah
melamun.” Dani memangkas lamunanku. “Ini kesempatanmu untuk bisa menjadi
pegawai pemerintahan. Jangan kau tolak lagi seperti yang sudah-sudah. Kalau
masalah amplop, tidak perlu kau fikirkan, biar aku yang bantu. Kau sahabat
karibku, bahkan sudah seperti saudara bagiku. Dulu, kalau bukan karena
bantuanmu mungkin aku sudah gagal jadi sarjana dan belum tentu bisa sukses
seperti sekarang. Aku hanya ingin membantumu Man, sungguh.”
“Aku masih bimbang Dan.
Haruskah aku ikut terseret dalam arus birokrasi busuk yang sangat bertentangan
dengan jiwaku, bertentangan dengan kata hatiku?” Akhirnya aku menjawab.
“Kondisi yang ada saat ini
memang seperti itu kawan. Kita tidak bisa mengingkarinya. Apalagi kita sekarang
sudah bukan mahasiswa lagi. Jadi aku pikir bolehlah tidak terlalu idealis lagi.
Saat ini kondisi yang kita hadapi sudah berbeda, sudah banyak yang menjadi
pertimbangannya. Masa depan kita, keluarga kita, dan juga harapan-harapan orang
tua yang telah menghabiskan sekian banyak biaya untuk kita selama ini.” Kata
Dani.
“Maksudmu, apakah kita harus
melakukan apa yang dulu kita haramkan? Aku tidak bisa seperti itu Dan.”
“Bukan begitu. Aku hanya
berfikir sederhana saja, daripada orang yang bermental busuk dan bobrok yang
diterima lebih baik orang dengan sifat yang baik. Kau mungkin tidak sadar bahwa
dengan penolakan-penolakan yang pernah kau lakukan, secara tidak langsung, kau
telah memberi kesempatan bagi mereka yang serakah untuk menggerogoti luka
negeri yang telah bernanah. Sementara, andai kau berada di dalam struktur itu,
paling tidak kau bisa ikut meminimalisir kebobrokan itu walaupun tidak akan
bisa menghentikan sepenuhnya.” Ujar Dani.
“Tapi yang jadi persoalannya,
mengapa harus diawali dengan cara yang salah Dan?”
“Ya sudahlah, aku tidak tahu
harus mengatakan apa lagi padamu. Sebagai sahabatmu aku hanya ingin
mengingatkan bahwa sudah puluhan kali kau tolak kesempatan yang datang padamu.
Kau tidak akan pernah tahu berapa kesempatan lagi yang menjadi jatahmu. Jika
kesempatan saat ini merupakan kesempatan yang terakhir, maka jangan pernah kau
sesali dikemudian hari. Yang pasti, aku tahu betul bahwa kau adalah tumpuan
harapan orang tuamu.”
Kebimbangan makin memuncak
dalam jiwaku. Keinginan untuk mewujudkan harapan orang tua dan keinginan
mempertahankan prinsip hidup saling seret-menyeret. Salah satu pilihan
sepertinya akan menumbalkan pilihan lainnya. Jika saran Dani yang ku
perturutkan maka tergadailah rasanya moral dan jiwaku, akan menjadi tumbal dan
hancur leburlah prinsip hidup yang telah kubangun bertahun-tahun. Tapi jika
prinsip hidup yang aku pertahankan, maka harapan orang tuaku yang akan menjadi
tumbal dan entah kapan aku bisa mewujudkan harapan mereka.
Aku benar-benar sulit untuk
mengambil keputusan. Bahkan setelah Dani pergi pun aku masih saja bergelut
dengan kebimbangan. Pertimbangan-pertimbangan yang tadi diucapkan Dani
terngiang-ngiang silih berganti. Dani lah satu-satunya sahabatku yang tidak
pernah bosan mengunjungiku dan memberi pertimbangan. Padahal kawan-kawan yang
lain telah menghilang begitu saja. Mungkin mereka muak dengan sikapku yang
katanya keras kepala, sok alim, sok suci, dan sok idealis. Sementara aku
sendiri tidak begitu paham dengan semua yang mereka tuduhkan padaku itu.
Pada dasarnya aku hanya tidak
ingin ikut menjadi golongan orang-orang yang suka menjilat ludah sendiri. Dulu,
kami yang berteriak dan menuntut agar negeri ini bersih dari segala bentuk
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, nyatanya sekarang, kawan-kawan yang dulu
sama-sama berteriak itu malah pasrah pada keadaan dan ikut menjadi aktor
penting dalam menyuburkan sistem suap-menyuap. Alasan mereka paling-paling
karena terdesak oleh keadaan. Wajar saja kalau muncul kesan bahwa yang suka
berteriak itu adalah orang-orang yang iri dan belum mendapat kesempatan. Sempat
terfikir olehku, jangan-jangan memang begitu adanya?
Aku pandangi dinding ruangan
yang putih polos. Warna putih sering dianggap sebagai simbol sesuatu yang
bersih, lambang kesucian. Namun bagiku lambang kesucian itu adalah bayi, bukan
sebuah warna apa pun. Warna hitam tanpa bercak putih juga akan terlihat bersih tapi
belum tentu suci. Demikian juga halnya dengan warna-warna lainnya. Sukar untuk
mengetahui apa yang ada di balik tiap-tiap warna itu. Lain halnya dengan bayi.
Seorang bayi, walau memiliki cacat di tubuhnya, atau hasil hubungan haram
sekali pun, bayi itu tetap bersih dan suci.
Ah, aku tidak peduli dengan
semua itu. Yang pasti aku masih terombang-ambing antara ya dan tidak. Semakin
kucerna ucapan-ucapan Dani, maka makin menggunung pula rasa muakku akan realitas
hidup saat ini. Aku benar-benar heran, apakah benar-benar tidak ada lagi secuil
tempat saja untuk berkembangnya sesuatu yang disebut kejujuran? Jika benar
demikian, maka Dani lah yang menang. Tapi aku tidak sepenuhnya kalah. Sebuah
keputusan sudah menggumpal dan aku sangat yakin dengan keputusan itu. Dalam
hati aku berbisik, lemah. “Maaf Mak..!?”.
***
Maninjau,
04.08.’08
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Dream Motorcycle

Suzuki













.jpg)

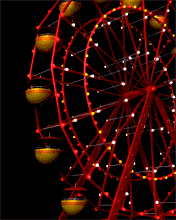








Tidak ada komentar:
Posting Komentar