Pagi baru saja menyambangi bumi. Embun-embun juga masih betah bermain-main di ujung-ujung lancip rerumputan. Tapi, ku dapati, Dira sudah duduk termenung di tepian Danau Maninjau. Matanya memandang jauh ke tengah danau, seakan sedang mengharapkan sesuatu keluar dari dasar danau.
Rasa ingin tahu membawaku melangkah mendekatinya. Tapi Dira hanya acuh. Bahkan saat aku duduk di sampingnya pun ia tetap acuh. Padahal biasanya ia selalu antusias dengan keberadaanku. Jika sudah bersamaku, ia selalu bercerita tentang semua kisah yang pernah singgah padanya.
Ya, begitulah biasanya. Dira tidak pernah ragu bercerita tentang apa pun padaku. Aku rasa, mungkin karena ketika ia sedang bercerita aku selalu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Aku memang tidak pernah memperlihatkan kebosananku padanya, walau terkadang ceritanya membuatku bosan juga.
Suatu ketika ia menceritakan pengalamannya saat dulu diajak ayahnya ke kota. Katanya, banyak keanehan yang ia lihat selama di kota.
“Contohnya apa?” tanyaku memancing ingatannya.
“Hmm, apa ya? O iya, di kota banyak anak-anak seusia Dira yang meminta-minta uang. Kata ayah, mereka itu pengemis dan tidak sekolah. Tapi mengapa mereka tidak sekolah ya?” Dira mengakhiri kalimatnya dengan sebuah pertanyaan yang entah ditujukan pada siapa.
“Itu karena orang tua mereka tidak mampu menyekolahkan mereka. Makanya, Dira harus rajin sekolah.” Aku menjawab seadanya. Sementara, dalam fikiranku, aku teringat dengan anak-anak jalanan yang makin lama makin menjamur di kota-kota. Dan keberadaan mereka seakan luput dari perhatian negara. Mungkin ada benarnya juga komentar iseng temanku di kampus dulu, bahwa di negara ini anak yatim dan anak-anak terlantar dipelihara di jalanan negara. Padahal, semestinya, mereka itu dibiayai dan menjadi tanggungan negara, bukan malah menjadi tunggangan tokoh-tokoh politik saat memperebutkan kursi pejabat negara.
“Uda…Uda…!!” sebuah tepukan kecil mendarat di bahuku. Aku tersentak.
“Kok bengong sih?” Dira cemberut, mungkin karena merasa diacuhkan.
“Uda lagi berfikir ra, bukannya bengong.”
“Masa anak manis dan pintar lagi bercerita, uda malah bengong.” Sambungku. Dan Dira pun kembali tersenyum.
Begitulah biasanya. Tapi pagi ini sikap Dira sangat lain. Ia duduk bermenung di tepi danau. Sesuatu, yang kutahu, tidak pernah dilakukannya. Malah ia yang sering menegurku saat aku sedang larut dalam lamunan.
Dira sangat dekat denganku. Sepertinya ia telah menganggapku sebagai saudara kandungnya sendiri. Padahal aku hanyalah salah seorang pekerja ayahnya. Sebulan yang lalu aku sengaja datang ke daerah ini untuk melakukan penelitian. Saat aku kehabisan biaya hidup, maka aku melamar kerja pada juragan Khaidir, ayah Dira. Hasilnya, jadilah aku sebagai salah seorang pekerja juragan Khaidir yang bertugas memberi makan ikan karamba. Tiap hari aku harus mendayung biduk untuk sampai ke karamba. Awalnya aku agak takut, karena aku tidak pandai berenang. Jika biduk terbalik maka bisa tamatlah riwayatku. Diwaktu senggang, setelah memberi makan ikan, Diralah yang sering menemaniku. Kadang ia sengaja datang ke pondokku hanya untuk bercerita. Tapi pagi ini ia begitu aneh.
“Sejak kapan Dira suka bermenung.” Pikirku. Kehadiranku bahkan tidak berarti apa-apa baginya. Agaknya ada masalah yang sangat membebani fikiran anak itu. Sekian waktu aku bergelut dengan fikiranku dan mengira-ngira masalah yang sedang membebani Dira. Tapi aku benar-benar tidak bisa memperkirakannya. Sepertinya aku harus bertanya langsung padanya.
Aku geser dudukku agar lebih dekat dengannya. Tapi ketika aku bertanya, aku jadi terkejut, karena suaraku tidak keluar sedikit pun. Kutarik nafas dalam-dalam dan kuulangi usahaku untuk bertanya. Tapi tetap saja aku tidak bisa bersuara. Kucoba teriak, suaraku tercekat saat sampai di tenggorokan. Aku benar-benar bingung. Kuhentikan usahaku untuk bisa bersuara. Kuulurkan tanganku ke pundaknya. Tapi belum sampai tanganku menyentuh pundaknya, tiba-tiba Dira mengeluarkan sehelai kertas dari kantong bajunya. Aku terlonjak dari dudukku, gerak tanganku yang akan menyentuh pundaknya menjadi tertahan. Aku kenal betul dengan kertas yang ada di tangan Dira itu.
Dira acuh saja. Ia membuka lipatan kertas itu dan membaca kalimat-kalimatnya dengan pelan.
“Lelaki itu terbujur di pagi hitam
Sekujur tubuhnya robek penuh luka
Tapi, ia masih mampu bernafas, walau pelan
Lelaki itu terhempas dalam derita
Anak-anak terbaiknya sembunyi entah dimana
Sehingga yang tersisa hanyalah anak-anak terliciknya
Lelaki itu memuntahkan darah
Ia telah menjadi tumbal anak-anaknya yang serakah
Dan, jiwanya pun kembali terjajah
Lelaki itu terbujur di pagi hitam
Ia bernama Indonesia
Yang terlahir dari rahim Pertiwi
(DMT. 02.08.’08)”
Dira melipat kertas itu, lalu dimasukkannya kembali ke dalam kantong bajunya. Air matanya mengalir di pipinya. Sementara, aku hanya mematung keheranan. Aku ingat betul bahwa barisan kalimat-kalimat yang dibaca Dira itu adalah puisi yang kutulis dua hari yang lalu. Tapi bagaimana bisa berada di tangan Dira? Seingatku aku tidak pernah memberikan puisi itu padanya. Dan aku juga yakin anak sekecil itu tidak akan paham dengan makna yang terkandung di balik kata-kata puisi itu. Puisi yang terlahir dari kegelisahan jiwaku akan sebuah negeri. Aku belum sempat memberi judul puisi itu. Bahkan saat bidukku terbalik pun puisi itu masih tak berjudul.
Air mata Dira masih berderai. Riak-riak danau yang gelisah pun tidak sanggup mengabarinya tentangku. Dira kehilangan aku, sosok tempatnya bercerita. Saat matahari makin nyata, aku pun segera sirna.
***
Maninjau, 02.08.’08













.jpg)

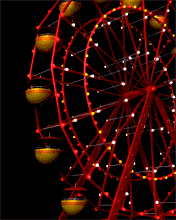












Tidak ada komentar:
Posting Komentar